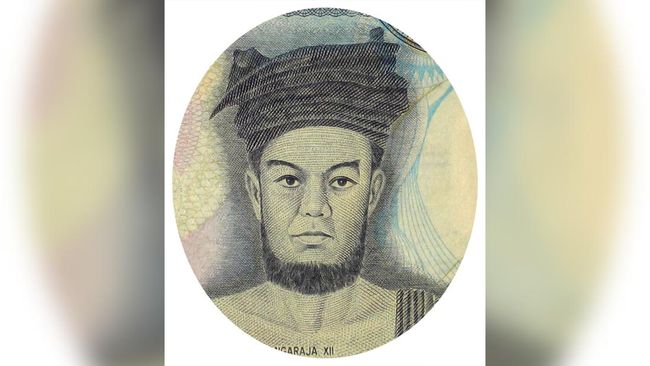Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, kita diajak merenung kembali: apakah sila-sila yang menjadi fondasi bangsa ini sungguh mengakar dalam kebijakan dan praktik pembangunan nasional kita hari ini? Laporan investigatif tentang bisnis karbon hutan Kalimantan memberi jawaban yang getir.
Di atas kertas, perdagangan karbon adalah solusi canggih untuk merespons krisis iklim. Namun di lapangan, ia justru menjelma menjadi bentuk baru dari ekstraksi sumber daya –dilakukan oleh para taipan dan korporasi besar yang berebut konsesi jutaan hektare hutan Kalimantan, dengan dalih restorasi dan konservasi. Padahal, sebagian besar dari mereka sebelumnya juga berperan dalam mendorong deforestasi besar-besaran lewat industri kayu, sawit, dan tambang.
Warga adat dan masyarakat desa seperti Lungkun Layang dan Madara yang hidup berdampingan dengan hutan selama puluhan tahun, kini justru menjadi korban dari gelombang baru konsesi karbon. Kampung mereka yang hendak dipindahkan demi akses infrastruktur justru terblokir oleh izin kehutanan korporasi. Mereka yang menggantungkan hidup dari rotan, kayu, atau tambang rakyat, dipaksa menyerahkan tanah ulayat demi “konservasi karbon” yang asing bagi kehidupan sehari-hari mereka.
Ketimpangan dan Ketidakadilan Sosial
Fenomena ini menggambarkan dengan jelas kegagalan mewujudkan sila kelima Pancasila –Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bukannya memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pelestarian lingkungan, negara justru lebih memilih membuka ruang bagi pemodal besar, bahkan yang memiliki afiliasi dengan konglomerat lama yang sebelumnya mengeruk sumber daya alam secara eksploitatif.
Iming-iming uang ganti rugi, insentif karbon, dan proyek-proyek “ramah lingkungan” tak jarang menjadi bentuk lain dari peminggiran warga lokal. Bahkan beberapa warga dikenai biaya untuk membeli bibit tanaman –sebuah paradoks ketika tanah dan hutan yang mereka jaga turun-temurun justru diklaim oleh korporasi luar.
Demokrasi Tanpa Partisipasi
Pancasila juga mengamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, banyak warga mengaku tidak benar-benar diberi ruang partisipasi dalam proses perizinan dan perencanaan proyek karbon. Syarat FPIC (persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan) hanya menjadi formalitas belaka.
Sementara itu, nama-nama besar seperti keluarga Wijaya (Sinar Mas), Rusli (Integra), hingga Triputra Group, kembali muncul sebagai pemegang saham dan penggerak utama proyek-proyek karbon. Ini mengukuhkan bahwa transformasi ekonomi hijau di Indonesia bukan sedang menciptakan keadilan ekologis, melainkan memperpanjang dominasi oligarki ekonomi dengan wajah baru.
Di Mana Etika Lingkungan dan Keutuhan Sosial?
Semangat kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semu ketika hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal dikorbankan atas nama target pengurangan emisi. Padahal, keberhasilan konservasi sejati hanya bisa dicapai dengan melibatkan warga sebagai subjek utama, bukan objek dari proyek-proyek ambisius yang dikendalikan dari ruang rapat di ibu kota atau luar negeri.
Penutup: Kembali ke Pancasila
Bisnis karbon bisa menjadi peluang baik, jika dikelola dengan adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal. Namun saat ini, kita belum melihat praktik itu berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, memperingati Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremonial, tetapi mesti menjadi panggilan untuk mengembalikan etika, keadilan, dan partisipasi rakyat dalam tata kelola sumber daya alam.
Hutan bukan sekadar angka ton CO₂ di pasar karbon global. Ia adalah ruang hidup, identitas budaya, dan sumber kehidupan jutaan warga Indonesia. (FR)
Foto : Hutan Kalimantan. Antara/Fiqman Sunandar